- Opini
SALAH satu upaya untuk memperbaiki pembangunan Aceh di masa akan datang dilakukan melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Aceh (RTRW). Rencana tata ruang ini ditetapkan dengan qanun sehingga menjadi dasar hukum baik untuk eksekutif, legistatif maupun yudikatif. Penetapan dengan qanun ini menjadi pedoman dalam penetapan, evaluasi pola dan struktur ruang maupun pemanfaatan ruang Aceh sesuai peruntukannya. Pemerintah Aceh mempunyai peran dan kewenangan sangat besar untuk penyusunan RTRW Aceh ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010 yang memberikan kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di provinsi.
Isu RTRW Aceh menjadi sangat krusial, karena akan menentukan Aceh masa depan, apalagi jika dikaitkan dengan batas waktu penyelesaian paling lambat akhir Oktober 2010. Jika hal tersebut belum ditetapkan dalam suatu qanun, maka dikhawatirkan Aceh akan menggunakan RTRW atau TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) lama. Masih banyak persoalan dan teka-teki yang belum terjawab antara lain terkait dengan masyarakat yang mendiami kawasan hutan, tata kelola hutan mukim, jaminan penyediaan lahan agar tidak timbul konflik baru, kawasan penyangga (buffer zone) pada wilayah rawan bencana dan lain-lain.
RTRW Aceh ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan produk-produk perencanaan lainnya termasuk Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2010-2025. Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan, sehingga pembangunan yang dijalankan sesuai dengan ruang dan peruntukannya untuk Aceh jangka panjang. Persoalan selama ini, pembangunan Aceh tidak didasarkan pada suatu perencanaan jangka panjang yang terintegrasi dan bersifat strategis atas dasar hasil kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keberlangsunganya untuk generasi Aceh akan datang.
Karena itu dalam penyusunan RTRW Aceh ini harus benar-benar dapat mengakomudasi kepentingan Aceh secara keseluruhan untuk jangka panjang dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable principle). Prinsip-prinsip ini akan mendorong pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi akan datang.
Demikian juga dengan pemanfaatan kawasan lindung harus menganut prinsip-prinsip konservasi melalui pemanfaatan, pengawetan dan upaya untuk mempertahankan flora dan fauna yang terancam punah dan dilindungi. Kawasan lindung ini bukan berarti tidak bisa dikelola secara ekonomis, justru di negara-negara maju pemanfaatan jasa konservasi ini memberikan nilai pendapatan dan peluang usaha bagi negara apabila dikelola secara serius dan profesional seperti yang ditunjukkan Korea Selatan dengan Taman Nasional Seoraksan maupun sejumlah kebun raya lainnya.
Kawasan budidaya perlu dicadangkan sebagai lahan usaha masyarakat melalui pemanfaatan hutan produksi, Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun dengan memproduksi Hutan Tanaman Rakyat lainnya. Areal Penggunaan Lain (APL) dapat dipergunakan untuk kepentingan usaha perkebunan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Penyusunan RTRW Aceh harus berbasis pada kearifan lokal/adat yang dimiliki masyarakat setempat. Pada masyarakat tempo dulu sudah dikenal pengelolaan hutan berbasis mukim (hutan mukim) sebagai level pemerintah terendah di Aceh. Hutan Mukim di bawah daulat imuem mukim ini harus dibangkitkan kembali eksistensinya, demikian juga dengan peran pawang uteun. Pada sejumlah negara maju justru 75% pengelolaan hutan dikembalikan kepada masyarakat dengan insentif yang diberikan negara, sehingga masyarakat ikut terlibat aktif memelihara dan mengelola hutan, tidak seperti Indonesia, khususnya Aceh yang selama ini dikelola pihak swasta dan negara yang membiarkan lahan-lahan subur terlantar dan bahkan akibatnya kebijakannya membawa bencana bagi masyarakatnya seperti banjir bandang dan tanah longsor. Persoalan lain menyangkut daerah kosong (enclave) masyarakat dalam kawasan konservasi seperti pada Kawasan Ekosistem Leuser.
Masyarakat dalam kawasan konservasi ini harus dapat berperan sebagainya penyangga kawasan hutan, bukan sebagai perusak seperti yang diasumsikan banyak pihak selama ini. Perubahan paradigma untuk menerapkan masyarakat lokal/adat sebagai bagian dari ekosistem harus didorong, supaya upaya penguatan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dan pelestarian ekosistem di sisi lain dapat berjalan bersama-sama
Pada saat ini para pelaku pembangunan di Aceh (SKPA, DPRA, pemerintah kabupaten/kota, CSO dan masyarakat sipil lainnya) belum satu visi merumuskan persoalan tersebut ke dalam RTRW Aceh. Hal tersebut dapat dilihat dari keinginan Tim Sekretariat Aceh Green untuk menambah kawasan hutan lindung sekitar 600 ribu Ha. Sementara di sisi lain SKPA dan pemerintah kabupaten/kota mengusulkan areal konversi cukup luas untuk penggunaan lain dalam rangka menunjang kesejahteraan rakyatnya.
Karena persoalan-persoalan tersebut di atas, diyakini nanti pasca-penetapan RTRW Aceh ada sejumlah konflik pemanfaatan ruang akan menghadang Aceh, banyak para pihak dan komunitas masyarakat dalam kawasan hutan akan berhadapan dengan penegakan hukum karena dicap sebagai perambah hutan dan penguasaan lahan bertentangan dengan hukum. Bahkan tidak menutup kemungkinan institusi negara yang mengawal proses penetapan RTRW Aceh akan dituntut oleh masyarakat yang merasa dirugikan atas kebijakan penetapan tata ruang karena masyarakat setempat sudah tinggal di dalam kawasan hutan selama puluhan tahun.
Penyelesaian konflik ini dapat dilakukan sambil berjalan melalui pendekatan-pendekatan pemindahan (resetlemen) masyarakat dari kawasan hutan atau deregulasi sistem pengelolaan hutan. Tetapi lagi-lagi ini dihadapkan pada kesulitan untuk penyediaan lahan, kalaupun ada harus melalui kompensasi sehingga menyedot banyak dana, energi, pikiran dan waktu. Kasus seperti ini pernah terjadi di Aceh, di mana masyarakat tidak mau pindah walaupun sudah terjadi bencana seperti pada masyarakat sekitar pantai yang terkena tsunami atau masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser yang terkena banjir bandang.
Melihat persoalan di atas, seluruh komponen Aceh harus menyatukan visi dan melihat Aceh secara jernih untuk jangka panjang. Materi RTRW Aceh harus menjadi pedoman semua pihak untuk pemanfaatan ruang/tapak Aceh serta memberikan perlindungan terhadap semua kepentingan masyarakat, termasuk mengantisipasi sebagai daerah rawan bencana, semoga.
* Penulis (keduanya) adalah pemerhati pembangunan dan Lingkungan, berdomisili di Banda Aceh
Isu RTRW Aceh menjadi sangat krusial, karena akan menentukan Aceh masa depan, apalagi jika dikaitkan dengan batas waktu penyelesaian paling lambat akhir Oktober 2010. Jika hal tersebut belum ditetapkan dalam suatu qanun, maka dikhawatirkan Aceh akan menggunakan RTRW atau TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) lama. Masih banyak persoalan dan teka-teki yang belum terjawab antara lain terkait dengan masyarakat yang mendiami kawasan hutan, tata kelola hutan mukim, jaminan penyediaan lahan agar tidak timbul konflik baru, kawasan penyangga (buffer zone) pada wilayah rawan bencana dan lain-lain.
RTRW Aceh ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan produk-produk perencanaan lainnya termasuk Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2010-2025. Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan, sehingga pembangunan yang dijalankan sesuai dengan ruang dan peruntukannya untuk Aceh jangka panjang. Persoalan selama ini, pembangunan Aceh tidak didasarkan pada suatu perencanaan jangka panjang yang terintegrasi dan bersifat strategis atas dasar hasil kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keberlangsunganya untuk generasi Aceh akan datang.
Karena itu dalam penyusunan RTRW Aceh ini harus benar-benar dapat mengakomudasi kepentingan Aceh secara keseluruhan untuk jangka panjang dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable principle). Prinsip-prinsip ini akan mendorong pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi akan datang.
Demikian juga dengan pemanfaatan kawasan lindung harus menganut prinsip-prinsip konservasi melalui pemanfaatan, pengawetan dan upaya untuk mempertahankan flora dan fauna yang terancam punah dan dilindungi. Kawasan lindung ini bukan berarti tidak bisa dikelola secara ekonomis, justru di negara-negara maju pemanfaatan jasa konservasi ini memberikan nilai pendapatan dan peluang usaha bagi negara apabila dikelola secara serius dan profesional seperti yang ditunjukkan Korea Selatan dengan Taman Nasional Seoraksan maupun sejumlah kebun raya lainnya.
Kawasan budidaya perlu dicadangkan sebagai lahan usaha masyarakat melalui pemanfaatan hutan produksi, Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun dengan memproduksi Hutan Tanaman Rakyat lainnya. Areal Penggunaan Lain (APL) dapat dipergunakan untuk kepentingan usaha perkebunan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Penyusunan RTRW Aceh harus berbasis pada kearifan lokal/adat yang dimiliki masyarakat setempat. Pada masyarakat tempo dulu sudah dikenal pengelolaan hutan berbasis mukim (hutan mukim) sebagai level pemerintah terendah di Aceh. Hutan Mukim di bawah daulat imuem mukim ini harus dibangkitkan kembali eksistensinya, demikian juga dengan peran pawang uteun. Pada sejumlah negara maju justru 75% pengelolaan hutan dikembalikan kepada masyarakat dengan insentif yang diberikan negara, sehingga masyarakat ikut terlibat aktif memelihara dan mengelola hutan, tidak seperti Indonesia, khususnya Aceh yang selama ini dikelola pihak swasta dan negara yang membiarkan lahan-lahan subur terlantar dan bahkan akibatnya kebijakannya membawa bencana bagi masyarakatnya seperti banjir bandang dan tanah longsor. Persoalan lain menyangkut daerah kosong (enclave) masyarakat dalam kawasan konservasi seperti pada Kawasan Ekosistem Leuser.
Masyarakat dalam kawasan konservasi ini harus dapat berperan sebagainya penyangga kawasan hutan, bukan sebagai perusak seperti yang diasumsikan banyak pihak selama ini. Perubahan paradigma untuk menerapkan masyarakat lokal/adat sebagai bagian dari ekosistem harus didorong, supaya upaya penguatan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dan pelestarian ekosistem di sisi lain dapat berjalan bersama-sama
Pada saat ini para pelaku pembangunan di Aceh (SKPA, DPRA, pemerintah kabupaten/kota, CSO dan masyarakat sipil lainnya) belum satu visi merumuskan persoalan tersebut ke dalam RTRW Aceh. Hal tersebut dapat dilihat dari keinginan Tim Sekretariat Aceh Green untuk menambah kawasan hutan lindung sekitar 600 ribu Ha. Sementara di sisi lain SKPA dan pemerintah kabupaten/kota mengusulkan areal konversi cukup luas untuk penggunaan lain dalam rangka menunjang kesejahteraan rakyatnya.
Karena persoalan-persoalan tersebut di atas, diyakini nanti pasca-penetapan RTRW Aceh ada sejumlah konflik pemanfaatan ruang akan menghadang Aceh, banyak para pihak dan komunitas masyarakat dalam kawasan hutan akan berhadapan dengan penegakan hukum karena dicap sebagai perambah hutan dan penguasaan lahan bertentangan dengan hukum. Bahkan tidak menutup kemungkinan institusi negara yang mengawal proses penetapan RTRW Aceh akan dituntut oleh masyarakat yang merasa dirugikan atas kebijakan penetapan tata ruang karena masyarakat setempat sudah tinggal di dalam kawasan hutan selama puluhan tahun.
Penyelesaian konflik ini dapat dilakukan sambil berjalan melalui pendekatan-pendekatan pemindahan (resetlemen) masyarakat dari kawasan hutan atau deregulasi sistem pengelolaan hutan. Tetapi lagi-lagi ini dihadapkan pada kesulitan untuk penyediaan lahan, kalaupun ada harus melalui kompensasi sehingga menyedot banyak dana, energi, pikiran dan waktu. Kasus seperti ini pernah terjadi di Aceh, di mana masyarakat tidak mau pindah walaupun sudah terjadi bencana seperti pada masyarakat sekitar pantai yang terkena tsunami atau masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser yang terkena banjir bandang.
Melihat persoalan di atas, seluruh komponen Aceh harus menyatukan visi dan melihat Aceh secara jernih untuk jangka panjang. Materi RTRW Aceh harus menjadi pedoman semua pihak untuk pemanfaatan ruang/tapak Aceh serta memberikan perlindungan terhadap semua kepentingan masyarakat, termasuk mengantisipasi sebagai daerah rawan bencana, semoga.
* Penulis (keduanya) adalah pemerhati pembangunan dan Lingkungan, berdomisili di Banda Aceh

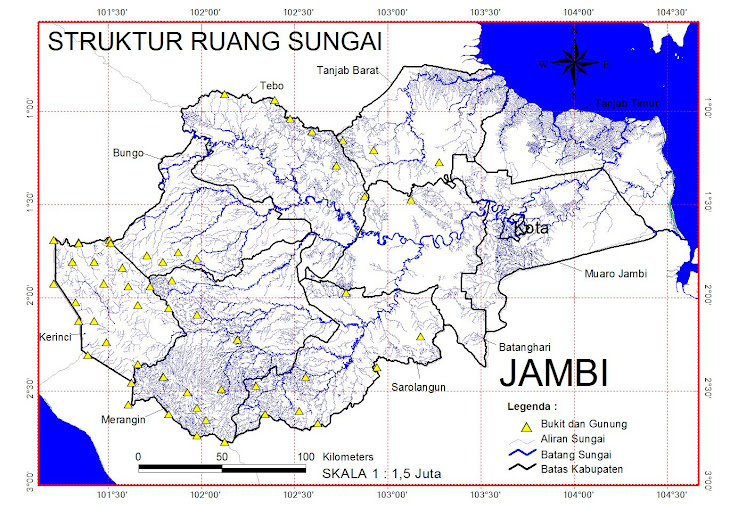



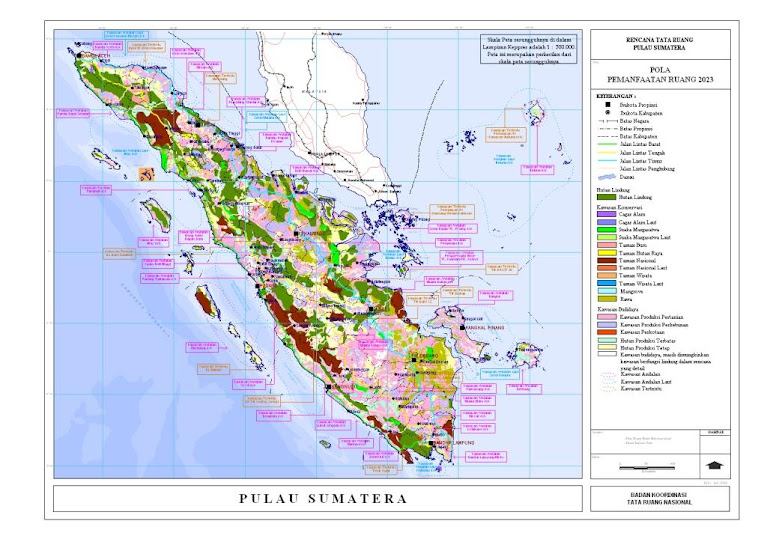
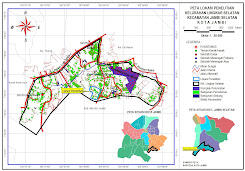





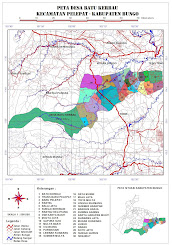
Tidak ada komentar:
Posting Komentar