
Laurensius Gawing[i]
Kerut dahi Apai Kudi (75 th) tampak begitu kentara, tatkala mendengar bahwa Kapuas Hulu mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi sejak tahun 2003[ii]. Walaupun jarak rumah panjang Sungai Utik di mana ia bermukim sekarang berjarak 75 Km dari Putussibau ibu kota kabupaten Kapuas Hulu, namun informasi ini begitu samar ia pahami. Sejak di deklarasikan tahun 2003, Pemda Kapuas Hulu belum memberi penjelasan kepada masyarakat adat Iban di rumah panjang Sungai Utik tentang apa dan bagaimana inisiatif tersebut muncul, dan seperti apa perkembangannya saat ini.
Belum genah mencerna informasi mengenai konsepsi kabupaten konservasi, kini Apai Kudi bersama khalayak umum di Kapuas Hulu dipusingkan dengan maraknya isu perubahan iklim terutama REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation). Situasi ini kian runyam ketika Kapuas Hulu kini menjadi wilayah ujicoba (demonstration activities) REDD oleh Fauna and Flora International (FFI) serta proyek bilateral Pemerintah Indonesia-Jerman bertitel “Forest and Climate Change Programe” (ForClime).
Kerut kening Apai Kudi, serta kebingungan masyarakat atas skema-skema yang dibangun oleh Pemda seperti konsep kabupaten konservasi, atau pun skema REDD yang konsepsinya datang dari luar, merupakan gambaran dinamika isu perubahan iklim di Kalbar secara umum. Bagaimana tidak, sejak diskursus perubahan iklim mengemuka di Indonesia seiring CoP[iii] ke 13 di Bali pada 2007, isu ini terus menggema tetapi anehnya hal ini tidak akrab dengan masyarakat Kalbar, khususnya Kapuas Hulu yang menjadi lokasi ujicoba.
Informasi tentang isu perubahan iklim terutama REDD menjadi elit, hanya milik Ornop konservasi dan instansi pemerintah terkait sektor kehutanan semata. Informasi seadanya yang tersebar ke masyarakat kerap kali menjadi bola liar dan tak terkawal baik oleh Pemda, sehingga pemahaman masyarakat mengenai REDD hanya berkisar mengenai kucuran uang yang datang dari negara kaya.
Minimnya asupan informasi tentang isu perubahan iklim (REDD) membuat masyarakat kerap bertanya-tanya, apa dan bagaimana REDD yang ramai diperbincangkan tersebut. Namun, pada saat yang bersamaan Kapuas Hulu tak memiliki banyak tempat bertanya mengenai hal tersebut, selain belum memiliki kelembagaan khusus seperti Pokja Perubahan Iklim/REDD, sulitnya publik mengakses informasi di Pemda menambah runyam pemahaman masyarakat tentang REDD, selain akses transportasi yang buruk.
Situasi ini tentunya sedikit teratasi jika keterlibatan masyarakat diutamakan dalam proyek ujicoba REDD di Kapuas Hulu, terutama yang berada di dalam dan sekitar area ujicoba. Namun keadaan ideal tersebut sulit digapai karena masyarakat adat dalam prakteknya tidak mendapat perhatian serius dari pengembang REDD dan Pemda, padahal, hutan yang menjadi lokasi ujicoba berada di wilayah adat (hutan adat) yang selama ini dijaga dan dikuasai oleh masyarakat adat.
Free Prior and Informed Consent (FPIC)[iv] yang dipercayai sebagai sebuah prinsip penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan dilakukan sebelum proyek dimulai, kenyataan yang terjadi tidak dilapangan tidaklah demikian. Masyarakat adat yang ada di dalam maupun sekitar wilayah ujicoba REDD menjelaskan bahwa, FPIC memang dipaparkan definisinya dalam presentasi melaui beberapa workshop yang dilakukan pemrakarsa REDD di kabupaten maupun kecamatan, namun hal tersebut tidak genah terpahami oleh peserta.
Riset LBBT[v] serta informasi masyarakat sekitar area DA menjelaskan bahwa, informasi FPIC secara umum dibagikan kepada masyarakat adat namun sesudah proyek mulai. Seperti contoh, MoU antara Pemda Kapuas Hulu dan FFI serta Macquarie Capital Groups Limited, diteken pada tanggal (22/8/2008) sedangkan proses-proses sosialisasi terkait FPIC dilakukan pada 2009 dengan pendekatan yang jauh dari memadai.
Simpang-siurnya informasi tentang REDD di masyarakat terutama mengenai kejelasan hak-hak dan akses atas hutan, memunculkan kecemasan pada masyarakat adat/lokal. Kecemasan mereka tentu sangat berdasar karena dilandasi oleh pengalaman empiris atas praktik konservasi model pemerintah, seperti taman nasional, hutan lindung dan lain-lain, yang menihilkan keberadaan masyarakat serta memutus relasi mereka dengan hutan dan tanah leluhurnya.
Pemutusan relasi sepihak antara masyarakat adat dan hutan melalui penetapan taman nasional yang tidak partisipatif sebagai salah satu contoh, berdampak buruk bagi kelangsungan tradisi dan identitas budaya masyarakat. Hutan bukan kumpulan tegakan pohon semata dalam pandangan masyarakat adat, bagi mereka, hutan adalah urat nadi kehidupan, Dayak Iban kerap menyebutnya Darah ngau seput kitae (darah dan nafas). Bersamaan dengan itulah, kearifan dan pengetahuan lokal tumbuh menyertai masyarakat adat guna menjaga dan mengelola sumberdaya alamnya. Praksis berbasis kearifan mereka, hingga kini mudah dijumpai pada komunitas masyarakat adat di Kapuas Hulu.
Sungai Utik merupakan satu model terbaik saat ini dalam mengelola wilayah adatnya, pada 2008 komunitas ini dianugerahi sertifikat ekolabel dari LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia) karena sukses mengelola hutan secara lestari.Yang menjadi kecemasan saat ini adalah, apalah artinya semua pengetahuan dan kearifan lokal tersebut jika pengembang REDD dan Pemerintah tutup mata, dan masih menganggap masyarakat adat/lokal lah perusak hutan sesungguhnya. Tudingan itu kerap kali muncul dan menjadi basis legitimasi pengelolaan kawasan konservasi (taman nasional)[vi] yang represif.
REDD, hingga kini menjadi kecemasan terbesar masyarakat adat karena berpotensi represif menyerupai model taman nasional, yang membatasi relasi masyarakat dan hutan. Jika tanpa penjelasan memadai dan pelibatan yang semaksimal mungkin, akan sulit mendapatkan model pelaksananaan REDD yang ideal serta bermanfaat bagi semua pihak. Artinya dukungan dari masyarakat adat sangat penting diwujudkan dalam skema yang dikembangkan saat ini. Menjamin hak-hak atas hutan, serta mengelaborasi kearifan (local wisdom) dan pengetahuan lokal (indigenous knowledge) dengan skema yang dibangun oleh dunia internasional saat ini, adalah kata kunci sukses tidaknya skema mitigasi dan adaptasi di Indonesia secara umum, dan Kalbar khususnya.
note :
- tulisan ini dimuat di buletin WG-Tenure
- Photo credit :L Tatang (Ppshk)
[ii] Dengan dasar SK Bupati no 144 tahun 2003 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten Konservasi, sejak 2003 Pemda gencar berupaya mewujudkan kompensasi atas usaha konservasi ini.
[iii] Conference of Parties, adalah sebuah kelembagaan yang merupakan ‘supreme body’ dan otoritas tertinggi dalam pembuatan keputusan Konvensi Perubahan Iklim, selain itu CoP merupakan pertemuan tahunan yang mengumpulkan semua negara pihak (parties) anggota konvensi.
[iv] Free, Prior and Informed Consent’ (FPIC) telah berkembang sebagai prinsip utama dalam jurisprudensi internasional berhubungan dengan masyarakat adat dan telah diterima secara luas dalam kebijakan sektor swasta atas ‘tanggung jawab sosial perusahaan’ dalam sektor seperti pembangunan bendungan, industri ekstraktif, kehutanan, perkebunan, konservasi, pencarian-genetika dan penilaian dampak lingkungan. Sehingga FPIC menjadi bagian penting Safe guarding bagi hak-hak masyarakat adat menghadapi proyek REDD.
[v] LBBT adalah sebuah Ornop yang bergerak di isu advokasi hak-hak masyarakat adat di Kalbar, pada tahun 2009-2010, melakukan dua riset mengenai masyarakat adat dan DA REDD di Kapuas Hulu terutama di wilayah sekitar Danau Sentarum dan Danau Siawan-Belida yang merupakan area ujicoba REDD oleh FFI
sumber : http://laurensgawing.blogspot.com/2010/08/jangan-ambil-hutan-kami.html

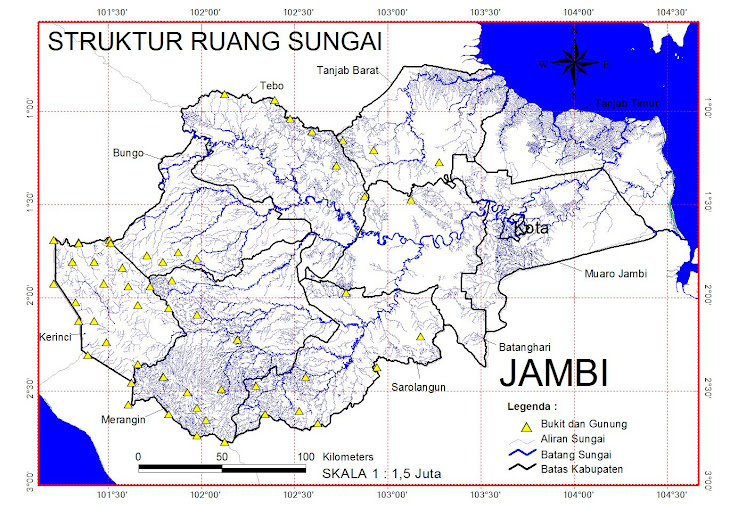



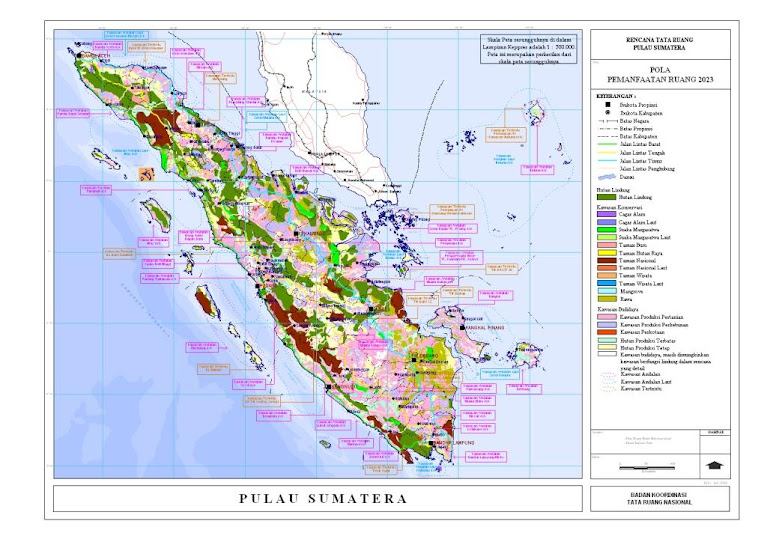
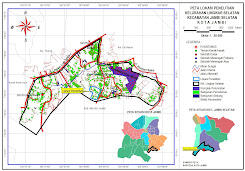





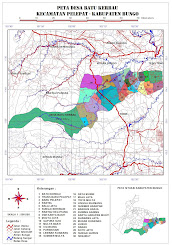
Tidak ada komentar:
Posting Komentar